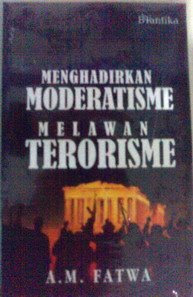Kiranya, citra Tomy Winata (TW) betul-betul sudah terpuruk dan mati di tangan para kuli tinta. Bisa dikatakan, pencitraan tersebut sudah berlangsung jauh-jauh hari sebelum meletusnya peristiwa unjuk rasa karyawan keamanan Artha Graha, Banteng Muda Indonesia (BMI), serta Forum Pemuda Peduli Pers (FPPP) ke kantor majalah
Tempo pada 8 Maret 2003 yang menghebohkan itu.
Nyatanya, memang demikian. Dalam kurun waktu Februari 1999 hingga Maret 2003 silam, hampir semua media mengangkat isu seputar Tomy Winata dengan
framing yang delegitimatif terhadap sosok pengusaha ini.
Pascareformasi, Tomy, - yang melakukan kerja sama bisnis dengan Yayasan Eka Paksi (YEKP) milik Angkatan Darat, - ini dilegitimasi melalui citra buruk ABRI dan bisnis militernya selama Orde Baru, kabar tentang adanya jaringan mafia
Gang of Nine atau Sembilan Naga, serta beberapa konflik hukumnya dengan sejumlah pengusaha.
Sedikit banyak, ini membuktikan, bahwa media turut andil dalam merangkai ingatan masyarakat tentang citra Tomy sebagai pengusaha yang amat dekat dengan pajabat militer dan polisi.
Sampai-sampai, media massa pun punya julukan tersendiri untuknya, yakni Tomy Winata sebagai
the godfather mafia yang menjalankan bisnis haram, mulai dari perjudian, narkoba, hingga penyelundupan. Dan dalam pandangan media itu, dengan kekuatan senjata dan ditamengi preman-preman, apapun bisa dilakukan Tomy di negeri ini, tak terkecuali jalan bisnisnya. Ia bahkan tak akan tersentuh kaki tangan hukum dan akan selalu lolos dari jeratnya.
Walhasil, setelah unjuk rasa pada 8 Maret 2003 di kantor
Tempo itu, Tomy secara resmi telah menjadi musuh media, yang akhirnya ditarik menjadi musuh publik. Sementara itu, kalangan jurnalis yang ditengarai oleh Goenawan Muhammad, Fikri Jufri, Todung Mulya Lubis, dan Harry Tjan Silalahi sendiri pun mendelegitimasikan citra Tomy itu dengan membangun gerakan wartawan melawan premanisme atau gerakan antipremanisme.
Melihat ini, ada dugaan, bahwa sebagian besar masyarakat kita hingga sekarang masih menerima secara pasif semua berita yang disiarkan media massa. Jika betul begitu, tentu saja ini cukup merisaukan. Apalagi, sekarang ini bertebaran berita di mana para wartawan penulisnya tak sekadar hanya sebagai pengamat, melainkan juga subyek yang tak terpisahkan dari realitas sosial yang diberitakannya. Mau tak mau, masyarakat perlu meluangkan waktunya untuk berhati-hati menyikapi tiap berita yang disajikan media.
Di sisi lain, sejatinya, sebuah media tetap menganggap khalayak sebagai pembaca yang kritis. Sebab, bukan tidak mungkin, pembaca tak mudah begitu saja menerima fakta yang disajikan media. Dan, belum tentu pembaca akan selalu menyimpulkan fakta yang sampai ke tangannya itu sesuai dengan kehendak wartawan penulis tersebut. Boleh jadi, pembaca sendiri sudah memiliki pertimbangan lain dalam menyikapi berita yang disiarkan media itu.
Artinya, para pengelola media, termasuk wartawannya sendiri perlu membayangkan, bahwa khalayak persnya adalah pembaca berita yang kritis. Karena kenyataannya, demontrasi massa yang terjadi di kantor
Tempo pada 3 Maret 2003 lalu itu bukanlah aksi pertama yang menimpa media massa di Indonesia.
Kasus yang menimpa tabloid Monitor pada 1990 itu, misalnya. Protes khalayak menimpa kalangan redaksinya, kantornya diobrak-abrik dan pemimpin redaksinya dituntut untuk diadili. Tiga tahun berikutnya, giliran
Tempo didemo oleh sejumlah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dalam kasus konflik
Tempo-Bursah Zarnubi.
Tepat setahun berikutnya, -pada 1994, Republika juga mengalami hal serupa. Koran tersebut didemo mahasiswa yang tergabung dalam Komite Antifitnah. Pada periode setelah reformasi 1998, - tepatnya pada 2000, nasib sama dialami kantor harian
Jawa Post di Jawa Timur yang diduduki GP Anshor.
Menilik berbagai kasus di atas, di mana pembaca melakukan unjuk rasa terhadap institusi pers dapat diartikan sebagai ketidakmampuan pers membayangkan khalayaknya sebagai pemaca yang kritis. Sebaliknya, jika para wartawan bisa membayangkan khalayaknya adalah pembaca yang kritis, pilihan faktanya akan disenangi pembaca. Dan bukan tak mungkin, beritanya akan senantiasa ditunggu-tunggu.
Maka, atas dasar itulah kiranya Saripuddin H. A dan Qusyaini Hasan yang merupakan dua aktivis Jasa Riset Indoensia (jAri) itu menuliskan buku
Tomy Winata dalam Citra Media - Analisis Berita Pers Indonesia. Namun, mengapa keduanya ”berani” memilih Tomy Winata sebagai objek penelitiannya kali ini? Sulit terbantahkan, bahwa Tomy Winata atau TW memang sosok fenomenal yang acap kali menjadi sasaran empuk media massa. Tentunya, warna-warni pemberitaan seputar dirinya menjadi begitu menarik untuk diselidiki.
Paradigma yang dipergunakan dalam studi kali ini bukanlah paradigma kritikal yang dipergunakan dalam melihat teks, dan bukan pula konstruktivis murni. Tetapi dengan menggunkana analisis framing Robert M. Entman, studi ini berusaha menggambungkan paradigma klasik yang melihat teks media sebagai realitas sesungguhnya dengan paradigma konstruktivis yang melihat teks media sebagai bentukan jurnalis media bersangkutan. Alhasil, kritik terhadap jurnalisme media yang dianalisis dilakukan sedikit mungkin, sedangkan kritik terhadap fakta yang dimuat dilakukan secara tidak langsung, - catatan kaki.
Pendangan resmi media seputar Tomy Winata dalam surat kabar harian atau koran tentu termuat dalam tajuk rencana atau editorial, sehingga inilah yang menjadi obyek studi. Artikel-artikel berita di koran tersebut tidak dijadikan obyek analisis lantaran tak dapat dinyatakan sebagai sikap atau opini resmi redaksi, disebabkan rentan dipengaruhi kinerja dan pengetahuan wartawan peliput atau penulisnya dalam memindahkan inti berita yang dinyatakan oleh suatu kejadian atau sumber berita.
Karena majalah tak memunyai tajuk rencana atau editorial, maka berita dalam laporan utamalah yang menjadi obyek studi. Pemilihan ini dilakukan, selain karena kebiasaan dalam analisis
framing di Indonesia sebagaimana dimuat dalam majalah Pantau, juga dengan pertimbangan bahwa artikel-artikel dalam laporan utama adalah kesatuan yang terintregasi, bukan sebagai produksi satu dua jurnalis di suatu media majalah. Laporan utama meruapakan produk bersama yang lahir di meja rapat redaksi.
Jadi diandaikan saja, tidak akan ada artikel yang kontradiktif (legitimatif dan delegitimatif terhadap citra atau profil seseorang) dalam sebuah laporan utama.
Dalam studi ini, benang merah antara artikel laporan utama itulah yang coba dilihat dengan analisis
framing Entman tadi. Karena Bab 4 dan Bab 5 tentang laporan utama majalah sebelum unjuk rasa 8 Maret 2003 itu dibedah dengan
framing Entman, maka Bab 6 tentang tajuk rencana atau editorial koran dibedah dengan analisis yang kualitatif-simbolik.
Cukup menarik, sebab dengan begitu pembaca bisa akan ikut mengeksplorasi teks secara lebih bebas. Dengan membaca Bab 4 dan Bab 5 sebelumnya, plus, analisis yang terurai di Bab 6 buku ini, sebenarnya telah dibuat untuk memudahkan pembaca menyimpulkan sendiri
framing tajuk rencana atau editorial dari perangkat
framing Entman.
Sebetulnya, kemudahan-kemudahan atau kekurangketatan metodologis itu dipilih untuk membantu memudahkan pembaca yang tidak bisa membaca analisis media. Bagi yang biasa membaca analisis media pun, pisau analisis yang digunakan dalam studi ini relatif tidak asing, sebab sering ditemui dalam analisis-analisis yang dimuat oleh Pantau, majalah kajian media dan jurnalisme yang diterbitkan oleh Institut Studi Arus Informasi (ISAI).
Tak lebih, studi dalam buku ini memang ingin menjawab soalan, bagaimana media melakukan pencitraan. Dan tentu saja, bagaimana media menghimpun, memilih, dan menuliskan fakta, melakukan politisasi bahasa, memberi label atau stigma tertentu pada sosok yang diberitakan. Namun, apakah buku ini bisa sedikit dijadikan sebagai wadah pembelajaran yang diharapkan bisa memperkuat kehidupan pers dan memperbaiki kondisi jurnalisme Indonesia? Semoga saja.